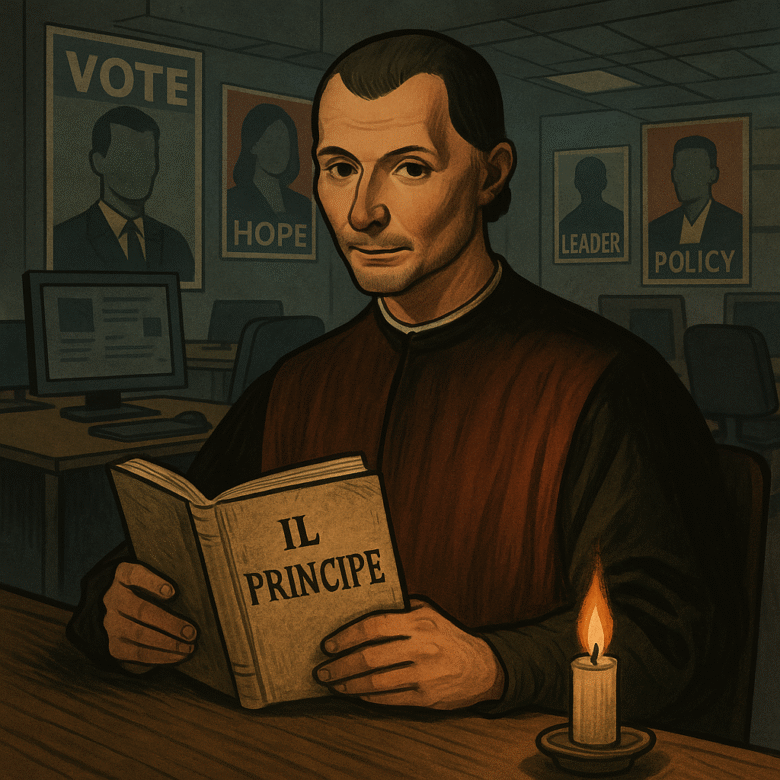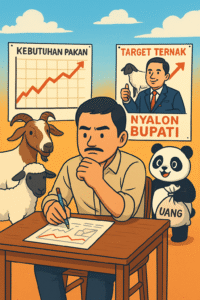Oleh: Penulis
Di dunia politik, baik saja tidak cukup. Bahkan kadang, terlalu baik itu berbahaya. Bukan cuma karena orang baik mudah dijatuhkan, tapi karena kebaikan itu sering kalah oleh strategi. Hal ini sudah dikatakan sejak 500 tahun lalu oleh seorang penulis asal Italia bernama Niccolò Machiavelli, lewat kitab legendarisnya: Il Principe (Sang Pangeran).
Machiavelli tidak bicara tentang moralitas. Ia bicara tentang kekuasaan, cara mempertahankan kekuasaan, dan mengapa idealisme tak selalu berguna di medan yang penuh intrik. Dalam bukunya, ia menulis dengan lugas, “Seorang pangeran yang ingin bertahan harus belajar untuk tidak selalu menjadi baik.”
Lalu kita lihat ke Indonesia. Lihat baliho-baliho. Lihat bansos-bansos. Lihat janji-janji. Politik di negeri ini tidak sedang memperdebatkan gagasan, tapi sedang menyusun strategi bertahan dan menang. Di sinilah Machiavelli menjadi relevan. Ia tidak mengajarkan pemimpin untuk jadi jahat. Tapi ia memperingatkan bahwa dunia terlalu kejam untuk dihadapi hanya dengan kejujuran dan keramahan.
Banyak yang mengutuk Machiavelli sebagai biang dari kelicikan politik. Tapi jika kita jujur, justru politik di sekitar kitalah yang membenarkan apa yang ia tulis. Coba tengok: berapa banyak pemimpin yang dipilih karena wajahnya ramah, janjinya manis, tapi tak tahu arah ketika sudah menjabat? Sebaliknya, ada yang tampak keras, dingin, bahkan dicurigai banyak hal—tapi mampu mengatur pemerintahan dengan stabilitas dan hasil nyata.
Machiavelli mengingatkan, pemimpin itu tidak perlu dicintai. Cukup ditakuti, asal tidak dibenci. Dalam satu kutipan yang paling terkenal, ia menulis: “Lebih aman bagi seorang pemimpin untuk ditakuti daripada dicintai, jika ia tidak bisa mendapatkan keduanya.” Apakah ini berarti penguasa boleh kejam? Tidak. Ini berarti penguasa harus realistis.
Cinta itu rapuh. Ia datang dan pergi. Tapi rasa takut? Ia membuat orang berhitung. Dalam konteks pemerintahan, ini berarti penguasa yang disegani akan lebih mudah mengontrol kekuasaan dan menjalankan program. Di Indonesia, kita sering terjebak memilih pemimpin yang terlalu ingin disukai. Pemimpin yang sibuk membuat konten, bukan kebijakan. Yang lebih takut kehilangan followers daripada kehilangan arah pembangunan.
Sementara itu, pemimpin yang bekerja dalam diam sering dituduh otoriter, terlalu teknokratis, atau tak populis. Padahal, dalam banyak kasus, justru merekalah yang mewariskan tata kelola yang lebih sehat. Machiavelli mungkin akan tersenyum melihat semua ini. Karena menurutnya, reputasi seorang pemimpin tidak dibangun dari janji, tapi dari tindakan dan hasilnya.
Dalam politik lokal, fenomena ini makin kentara. Kepala daerah sibuk menjalin relasi dengan penguasa pusat, membagi proyek pada loyalis, dan menciptakan narasi pencitraan yang rapi. Banyak yang tampak merakyat saat kampanye, tapi menjelma jadi elit begitu duduk di kursi. Machiavelli tidak akan heran. Ia akan bilang: ya wajar. Mereka sedang mengamankan kekuasaan.
Namun, ada hal penting yang sering dilupakan. Meski Machiavelli menganjurkan strategi kekuasaan yang “tidak baik”, ia juga menyarankan satu hal: jangan kehilangan dukungan rakyat. Seorang pemimpin bisa keras, bisa licik, bisa dingin, tapi jangan sampai kehilangan legitimasi. Tanpa rakyat, semua strategi akan runtuh. Karena pada akhirnya, bahkan penguasa paling kejam pun membutuhkan satu hal: pengakuan.
Pertanyaannya: apakah kita harus mengikuti Machiavelli? Haruskah pemimpin menjadi keras, manipulatif, dan penuh kalkulasi?
Jawabannya: tidak juga. Tapi kita bisa belajar bahwa dunia politik tidak semanis kata-kata kampanye. Ia adalah dunia kompromi, negosiasi, dan kadang pengkhianatan. Maka, daripada pura-pura idealis, lebih baik kita mendidik publik untuk memahami realitas kekuasaan. Bahwa menjadi pemimpin bukan soal malaikat vs setan. Tapi soal kompetensi, integritas, dan kemampuan bertahan di tengah tekanan.
Dan di sinilah rakyat harus menjadi lebih cerdas. Jangan menilai pemimpin hanya dari gaya bicara atau branding. Lihat rekam jejaknya. Lihat caranya mengambil keputusan. Lihat apakah ia benar-benar bekerja, atau sekadar numpang lewat untuk pemilu berikutnya.
Machiavelli menulis Il Principe bukan untuk rakyat, tapi untuk penguasa. Tapi hari ini, kita bisa membalik itu: membacanya sebagai peringatan bagi rakyat. Bahwa politik tidak netral. Bahwa kekuasaan tidak selalu adil. Dan bahwa kalau kita lengah, mereka yang paling “baik” di panggung bisa jadi yang paling “berhitung” di belakang layar.
Jadi, saat kita melihat politisi mencium bayi, memberi sembako, atau joget TikTok, kita berhak bertanya: ini tulus, atau taktik?
Karena dalam politik, seperti kata Machiavelli: hasil akhir sering kali lebih penting dari cara mencapainya. Tapi sebagai rakyat, kita masih bisa menentukan: hasil seperti apa yang kita mau?
————