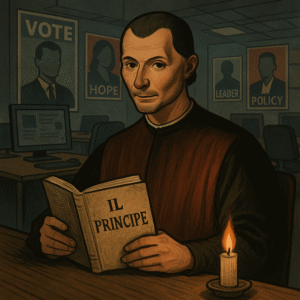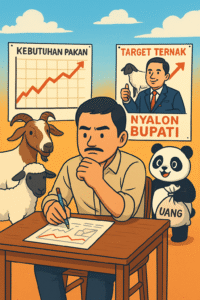Oleh : Penulis
Banyak orang ingin hukum dan politik dipisahkan. Seolah-olah hukum adalah ruang steril, dan politik hanyalah panggung kotor yang penuh kepentingan. Tapi di dunia nyata, keduanya seperti dua sisi pisau yang sama tajamnya—tak bisa dipisahkan, dan kadang saling melukai.
Di negara demokratis, hukum adalah instrumen pengatur kekuasaan. Tapi pada saat yang sama, politik adalah penentu siapa yang membuat dan menafsirkan hukum. Maka muncullah paradoks: hukum yang seharusnya netral bisa jadi alat politik, dan politik yang semestinya dikontrol hukum justru mengendalikan hukum itu sendiri.
Kita pernah melihat kasus hukum yang bergerak cepat ketika lawan politik tersandung. Kita juga melihat bagaimana undang-undang bisa berubah secepat mood elite parlemen. Lalu publik bertanya: mana yang lebih kuat, logika hukum atau logika kekuasaan?
Jawabannya: tergantung siapa yang sedang memegang gagang pisaunya.
Hukum sering dibungkus sebagai simbol keadilan. Tapi dalam praktiknya, ia juga alat. Dalam rezim yang otoriter, hukum dipakai untuk membungkam. Dalam sistem yang korup, hukum dijadikan tameng. Tapi bahkan dalam demokrasi, hukum bisa saja tunduk pada mayoritas yang sedang berkuasa. Inilah yang membuat politik hukum tidak pernah sepenuhnya bersih.
Sebaliknya, politik juga tidak bisa berdiri tanpa hukum. Ia butuh legitimasi, butuh legalitas, butuh prosedur. Tanpa hukum, politik berubah jadi kekerasan. Maka para politisi selalu berusaha menciptakan hukum yang “memihak”—bukan karena cinta hukum, tapi karena ingin kekuasaannya terlihat sah.
Pertarungan di ruang publik hari ini bukan hanya soal siapa benar dan siapa salah. Tapi siapa yang bisa memenangkan narasi hukum di arena politik, dan siapa yang bisa mengendalikan politik lewat instrumen hukum.
Ada aktivis yang dipenjara karena melawan tambang. Tapi ada pejabat yang bebas karena celah hukum. Ada masyarakat kecil yang dihukum karena mencuri, tapi korporasi yang merusak hutan hanya diminta “komitmen perbaikan”. Hukum seolah punya dua wajah: satu untuk mereka yang kuat, satu lagi untuk mereka yang lemah.
Tapi bukan berarti kita harus menyerah. Justru karena hukum dan politik saling mengkooptasi, rakyat harus sadar dan terlibat. Kritik pada politisasi hukum bukan berarti anti-pemerintah. Mengawasi pembuat undang-undang bukan berarti radikal. Justru inilah demokrasi: partisipasi yang aktif, bukan pasrah diam.
Hukum yang baik hanya bisa lahir dari politik yang sehat. Dan politik yang sehat hanya bisa bertahan jika hukum dijaga dari tangan-tangan kotor.
Maka, pisau itu memang bermata dua. Tapi di tangan rakyat yang cerdas, pisau itu bisa dipakai untuk membedah ketidakadilan, bukan untuk menusuk sesama.
———